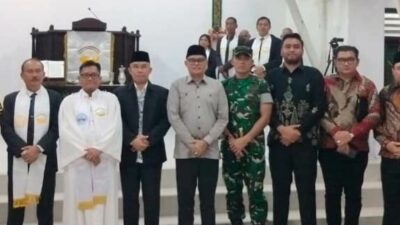Penataan cahaya karya Fathul Ajis dan arahan artistik Zaeni Mohammad menghadirkan ruang simbolik: sumur batu tempat Dende Tamari dihukum menjadi metafor atas kekuasaan yang membungkam, namun sekaligus tempat lahirnya cahaya perlawanan.
Pementasan ini melibatkan sejumlah aktor muda BAM yang tampil dengan intensitas emosional tinggi: Winsa, Dende Dila, Wulan Eryana Sain, Bagus Maulana, Hawa Metha, dan Febri Febrian. Manajemen panggung dipercayakan kepada Reza Ashari, dengan Mantra Ardhana sebagai penata suara, serta dukungan kru: Susan Damayanti, Lalu Farid, Syahrul Rozi, dan Akbar.
Para pemain menghidupkan tokoh-tokoh klasik dengan tubuh dan aksen lokal, menghadirkan keotentikan baru yang membedakan versi BAM dari adaptasi teater konvensional. Sorak dan tepuk tangan penonton di akhir pementasan menjadi bukti bahwa karya ini menyentuh sisi terdalam dari rasa kemanusiaan.
*Seruan Kemanusiaan*
Lebih dari sekadar pertunjukan, Dende Tamari adalah seruan kemanusiaan. Ia berbicara tentang keberanian untuk menentang ketidakadilan, tentang suara perempuan yang menolak tunduk pada kekuasaan yang buta. Ia mengingatkan kita bahwa di tengah dunia yang makin pragmatis, nurani tetap harus menjadi panglima.
“Seni bukan hiburan,” tutup Kongso Sukoco. “Seni adalah suara perlawanan, cermin kehidupan, dan panggilan hati nurani.”
Melalui Dende Tamari, BAM mengajak masyarakat untuk kembali percaya pada kekuatan perempuan, keberpihakan sosial, dan cinta pada kemanusiaan. Dari Lombok, pesan itu bergema: bahwa keberanian untuk berpihak pada kebenaran tak akan pernah lekang oleh zaman.
Didirikan lebih dari dua dekade lalu, BAM adalah kelompok teater independen di Mataram, NTB, yang konsisten mengeksplorasi teater berbasis naskah, riset sosial, dan pendekatan lokalitas. Dengan 63 pementasan hingga kini, BAM menjadi laboratorium kreatif bagi generasi muda dalam memahami seni sebagai jalan kesadaran sosial dan kebudayaan.