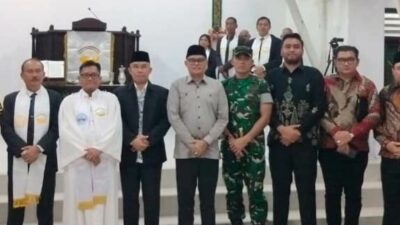Mataram — Bengkel Aktor Mataram (BAM) kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu komunitas teater paling konsisten di Nusa Tenggara Barat (NTB). Semalam, Sabtu 25 Oktober 2025, mereka menuntaskan pementasan lakon Dende Tamari di Gedung Tertutup Taman Budaya NTB, disaksikan oleh ratusan penonton yang memadati ruang pertunjukan hingga larut malam.
Pertunjukan ini sekaligus menjadi pementasan BAM ke-63, sebuah capaian yang menandai perjalanan panjang dan teguh kelompok teater yang berdiri di Mataram ini dalam menjaga napas seni pertunjukan di daerah.
Dalam sambutannya, Kepala Taman Budaya NTB, Lalu Surya Mulawarman, menyampaikan apresiasi mendalam terhadap konsistensi BAM dan relevansi pementasan kali ini. Menurutnya, Dende Tamari bukan hanya pertunjukan teater biasa, tetapi juga etalase seni pertunjukan yang mempertemukan lintas disiplin—teater, musik, seni rupa dan tradisi lokal.
“Pertunjukan ini adalah katalisator pembuka ruang dialog dan dialektika. Ia menjauhkan kita dari arogansi diri, bahkan dari arogansi personalisasi kekuasaan,” ujar Miq Surya. “Kegiatan seperti ini penting, karena seni mesti hadir sebagai ruang pertemuan gagasan dan kemanusiaan.”
Dalam konteks itu, BAM melalui sang sutradara, Kongso Sukoco, menegaskan bahwa teater bukan sekadar hiburan, melainkan alat untuk berpikir dan mempertanyakan. “Teater yang masih memedulikan unsur sastra akan selalu menekankan dialog dan pertanyaan. Dari situ lahir kesimpulan-kesimpulan baru dalam memahami relasi manusia,” ujarnya.
“Namun sekarang, tren teater mulai mengabaikan bahasa dan menggantinya dengan efek media. Kami ingin mengembalikan kekuatan kata dan rasa.”
Dende Tamari adalah adaptasi dari tragedi klasik Yunani Antigone karya Sophocles, yang kali ini dilahirkan kembali dalam konteks lokal Lombok. Pertanyaan mendasar yang melatari naskah ini tetap sama: apakah hukum buatan penguasa lebih tinggi daripada hukum moral dan kemanusiaan?
*Perempuan Sasak Menentang Kekuasaan*
Dalam versi BAM, sosok Antigone menjelma sebagai Dende Tamari—seorang perempuan Sasak yang berani menentang kekuasaan demi kemanusiaan. Ia menolak tunduk pada hukum yang menafikan nilai moral dan kasih sayang. Keberaniannya menimbulkan konflik besar yang berakhir tragis: Dende Tamari dihukum mati karena menentang hukum penguasa.
Sutradara Kongso Sukoco menjelaskan: “Tragedi disebut tragedi ketika peristiwa tragis menimpa orang baik. Dende Tamari adalah sosok yang melawan kekuasaan yang semena-mena. Ia akhirnya mati, tapi justru dari kematian itu lahir makna tentang kebenaran.”
Ada keberanian BAM menafsir ulang karya besar dunia ke dalam lanskap lokal, yaitu ‘menaklukkan Antigone’ ke dalam sosok Dende Tamari, perempuan Lombok yang membawa suara lokal untuk isu universal.
Kongso menimpali, “Itu menunjukkan bagaimana kita masih tertinggal dalam memahami paradigma kesetaraan gender. Padahal, ketika Antigone ditulis Sophocles ribuan tahun lalu, gagasan demokrasi dan kesetaraan sudah hidup.”
Kekuatan Dende Tamari bukan hanya pada narasi, tetapi juga pada perwujudan estetika yang berpijak pada bumi Lombok. Tembang tradisional, kostum daerah, dan alat musik lokal menjadi bagian dari tubuh pertunjukan.
Penonton diajak merasakan kegetiran tragedi Yunani dalam irama suling Sasak, dalam nyanyian yang lahir dari tanah sendiri.
Musik dan tata artistik menjadi jembatan antara dunia klasik dan realitas lokal. Para Musisi (tradisi) — *Lalu Prima Wira Putra*, Nurul Maulida, Ayutara Adelya, dan Nunuk Husnul—menghadirkan harmoni antara bunyi-bunyian tradisi dan atmosfer dramatik yang membangun emosi pertunjukan.